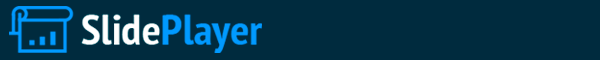
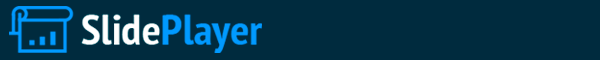
Ke Tanah Merah Tiga atau empat hari kemudian kami diberangkatkan dengan menumpang kapal yang lebih kecil lagi. Kapal ini milik Pemerintah yang disebut “kapal putih”, kapal yang biasa dipakai para pejabat untuk berturne ke berbagai pulau, nama kapal itu Albatros, ukurannya sangat lebih kecil dibanding dengan Melchior Treub. Sebab itu selama perjalanan kami merasa diayun gelombang sebesar gunung. Di kala kapal berada di bawah dan kami dapat melihat pucuk gelombang di atas kepala, ada seorang awak kapal nyeletuk bahwa di tempat ini ada pusar laut yang dapat menyedot kapal ke dasar laut. Bung Hatta dan Sjahrir hanya tersenyum saja, sedang saya ingin tahu apa sebabnya, karena sangat mengerikan. Kapal Albatros singgah di Pelabuhan Tuwal setengah hari dan menambah muatan untuk ke Tanah Merah, seperti ayam dan kelapa. Selanjutnya tak ada lagi tempat yang disinggahi. Kapal terus masuk ke sungai Digul pada waktu hari sudah gelap, sehingga kami tidak dapat melihat suatu apapun di kanan-kirinya, selain bayangan hitam. Baru esoknya kami dapat melihat rimba raya belantara dan terkadang menjumpai gubug di pohon-pohon, rumah penduduk asli yang masih primitif. Malam berikutnya, akibat terjadi banjir, kapal mengalami musibah, karena berlayar terlalu ke tepi. Di kala kami berbincang-bincang kami mendengar suara Bung Hatta berteriak-teriak “Awas-awas, awas.” Tetapi kapal sudah menabrak pohon yang menjulang di atas kali. Atap kapal tempat bernaung kami menjadi ringsek dan ada belandar atap yang terjatuh. Untung hanya menyerempet sedikit, kulit lengan saya lecet tidak berarti. Di kala teman-teman masih sibuk membenahi diri, Saudara Maskun mulai berkelakar, katanya: “Coba kalau Bung Hatta jadi kapten, kapal ini tak akan menabrak pohon”. Bung Hatta hanya tersenyum, Sjahrir tertawa agak lebar karena ia sedang memperhatikan saya yang sedang mondar-mandir mencari pipa rokok yang terlepas dari mulut saya. Pada malam itu tidak ada awak kapal yang berniat memperbaiki kerusakan, demikian pula kami yang menjadi penumpangnya, tidak juga berusaha pindah ke lain tempat dengan perkiraan bahwa kapal besok pagi pun akan sudah sampai di Tanah Merah.
Benar, di kala bangun di pagi hari, kami sudah dapat melihat sebuah rakit besar di pinggir kali yang dikatakan Pelabuhan Tanah Merah. Pada jam 8.00 pagi tanggal 22 Februari 1935, kami sudah menginjak daratan tempat buangan. Setelah acara serah terima dengan polisi yang mengantar kami sejak dari Tanjung Periok, kami dibawa ke daerah orang buangan (interneeringskamp), diantar oleh Lurah Tanah Merah yang dijabat orang buangan juga, bernama Budisucitro, bekas sekjen PKI lama. Kami dipersilakan memasuki rumah bekas toko Cina, dan rumah ini saja yang disediakan untuk Bung Hatta. Beberapa hari kami yang bujangan menumpang pada rumah Bung Hatta ini dengan tugas bergiliran masak di dapur. Pertama kali Bung Hatta dapat giliran menanak nasi dan saya yang harus mengangkatnya. Saya katakan kepada teman-teman bahwa ekonom kita tidak ekonomis. Bung Hatta tersenyum dan Sjahrir bertanya, “Mengapa?” saya jawab, “Nasinya hangus.” Kemudian Bung Hatta menepis, “Terbuang untuk orang, tetapi tidak terbuang untuk ayam,” ujar Bung Hatta. Dalam minggu pertama itu, Panitia Penerimaan menyodorkan rencana pertandingan persahabatan sepak bola. Dalam pertandingan itu Sjahrir menjadi barisan-muka-tengah, Bung Hatta dan Burhan di barisan belakang, sedangkan Murwoto penjaga gawang. Saya perhatikan Bung Hatta dapat menendang bola dengan kaki kanan dan kirinya, dan terkadang kepalanya yang hampir botak karena rambutnya mulai jarang itu dipergunakan juga untuk menerima bola. Dalam pertandingan ini barisan kesebelasan kami dicukur tiga gol dengan hanya dapat membalas satu gol saja. Di kala barang-barang kami sudah diperbolehkan diangkut dari gudang pelabuhan, ternyata Bung Hatta membawa buku sebanyak 16 peti. Sesaat sampai di rumah, saya bertanya, “Apakah Bung Hatta ini mau buka toko buku?” Beliau hanya menjawab dengan senyuman, tetapi Sjahrir yang selalu mendampinginya sejak teka-teki di Makassar, mengatakan kepada saya bahwa saya ini suka “ada-ada saja” kalau bicara. Moh. Bondan, Pribadi Manusia Hatta, Seri 6, Yayasan Hatta, Juli 2002