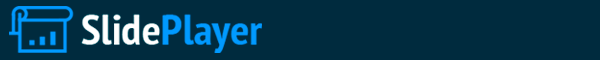
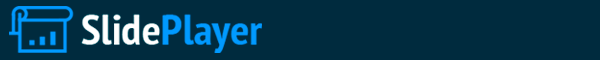
Uji-Ngaji Sewaktu kami bertiga: Kak Meutia, saya sendiri, dan Halida, masih kecil, Ibu menyarankan agar saya masuk sekolah Katolik. Waktu itu Ayah marah besar dan tidak setuju. Kata Ibu, baru sekali itu Ayah begitu marah. Namun Ibu mencoba menjelaskan, bahwa sekolah yang dimaksud terkenal sekali kedisiplinannya. Orang tua harus menanamkan disiplin dalam rumah, tetapi akan lebih baik lagi bila di sekolah soal disiplin juga ditekankan dengan keras. Akhirnya Ayah pun setuju, dengan catatan bahwa pelajaran mengaji saya lebih ditingkatkan. Setahun kemudian, Kak Meutia pindah ke sekolah Katolik yang lain yang lebih ketat lagi kedisiplinannya. Saya akhirnya ikut pindah ke sekolah yang sama. Halida si bungsu, tentu juga mengikuti jejak kami. Maka mulai dari tahun 1959 sampai masing-masing tamat SMA, kami bersekolah di sekolah Katolik. Walaupun begitu, tidaklah terjadi hal-hal seperti yang ditakutkan oleh kawan-kawan Ayah dan Ibu, bahwa anak-anak Bung Hatta akan terpengaruh oleh agama lain. Malahan kami meningkatkan disiplin mengaji pada ustadzah, yang datang ke rumah. Pengetahuan yang kami terima tentang agama Katolik di sekolah, dan bekal agama Islam yang kami dapat di rumah, maka pikiran kami tidak menjadi sempit, ataupun menjadi terpengaruh oleh agama lain. Sekolah Katolik bagi kami hanyalah merupakan sarana untuk menanamkan disiplin belajar yang tinggi, bersaing dengan teman dalam hal angka rapor, dan bekal melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi. Meskipun ibu guru ngaji dengan teratur mengajar kami, ayah belum juga puas. Sekali-kali beliau menguji anak-anak tentang kepandaian mengaji yang diperoleh. Saya termasuk salah satu di antara kami yang mendapat pengalaman khusus dalam hal mengaji ini. Pada suatu hari Ayah bertanya, “Gemala, sampai di mana pelajaran mengaji Gemala?” Saya menjelaskan seperlunya tentang pelajaran saya. Lalu beliau melanjutkan, “Besok pada jam empat sore Gemala kemari untuk Ayah uji.” Demikianlah keesokan harinya, pada jam empat sore Ayah telah berada di tempat yang sama: di kursi di beranda lantai kedua rumah kami. Ayah duduk membaca buletin Antara edisi sore, sambil minum teh dan kue-kue. Jadwal kerja Ayah sangat teratur. Setiap orang rumah telah mengetahui, di mana Ayah berada saat itu, tanpa harus mencari beliau ke setiap ruangan. Pada jam itu saya telah berada di atas. Saat itu perasaan saya tenang-tenang saja, sebab Ayah bukanlah orang yang menakutkan bagi anak-anak. Beliau tak pernah berbicara yang menyakitkan hati kepada anak-anak maupun kepada siapa saja di rumah. Tutur bahasa Ayah senantiasa penuh kasih sayang dan manis. Bilamana Ayah mengatakan akan “menguji”, maka syaratnya kami tidak boleh salah-salah. Salah sedikit tidak apa, tetapi bilamana salahnya agak banyak, berarti ujian tidak lulus! Biasanya kesalahan kami tidak membuat Ayah berang. Akan tetapi kejadian sore itu menjadi lain. Kala itu, selain menguji kemahiran mengaji saya. Ayah juga mengajarkan cara-cara baru dalam merangkaikan suku-suku kata Arab. Tulisan Ayah sungguh rapi dan bagus, sedangkan tulisan saya betul-betul sukar dibedakan, serba cakar ayam. Sudah tentu menyulitkan dalam membacanya kembali. Berkali-kali, saya sulit mengerti cara merangkai kata-kata Arab, yang ada di dalam kitab
Juz Amma. Akhirnya kesalahan sedikit makin menjadi-jadi, sehingga setiap kali Ayah harus mengoreksinya dengan ucapan yang benar. Lambat laun saya menjadi jengkel dengan diri sendiri dan menjadi makin ngawur. Ayah yang penyabar menjadi kesal dan akhirnya betul-betul marah. “Bagaimana anak ini, dari tadi salah terus-menerus! Perhatikan baik-baik, ini huruf apa, bodoh betul anak ini!” Mendengar bentakan yang mendadak, saya menjadi semakin gugup sebab wajah Ayah sudah “aduhai” kecutnya. Akhirnya Ayah membentak saya lagi: “Gemala sekarang turun ke bawah dan ingat kembali seluruh abjad! Nanti setengah jam lagi naik kembali kemari! Dan jangan membuat kesalahan yang serupa!” Saya sudah tidak berani memandang muka Ayah. Yang jelas, saya sudah berada di puncak senewen dan jengkel akan ketidakmampuan saya. Tetapi saya tidak terima juga bahwa Ayah saya memarahi dan mengatakan, “Bodoh betul anak ini!” Cepat-cepat saya membereskan buku dan lari turun ke bawah. Cepat-cepat pula saya membuka pintu kamar dan meledaklah tangis saya. Saking kesalnya, lalu saya mencari “liang persembunyian” di dalam lemari pakaian. Di tempat itu saya puaskan tangis saya. Setelah lebih dari setengah jam, saya tak juga kunjung datang, sedangkan biasanya anak-anak tidak pernah meleset dengan waktu, rupanya Ayah mempunyai firasat bahwa saya sedang ngambek. Perlahan-lahan Ayah turun ke bawah dan membuka pintu kamar saya sambil memanggil dengan manisnya, “Gemala… Gemala…!” Tetapi anak kecil yang sedang sedih dan jengkel terus saja bersembunyi, dengan tidak mempedulikan panggilan manis itu. Ayah rupanya merasa bahwa saya memang ada di ruangan itu. Hanya saja beliau tidak tahu, saya berada di mana. Ayah terus saja memanggil-manggil saya, sehingga akhirnya Ayah mendengar juga tangisan saya. Sewaktu saya mendengar langkah-langkah Ayah dekat lemari, kekesalan saya menjadi-jadi dan tangis protes saya semakin kuat untuk menarik perhatian. Ayah rupanya iba juga mendengar suara tangisan anaknya, sehingga membujuk saya dengan suara yang lebih manis lagi, minta supaya saya keluar dari dalam lemari. Perlahan-lahan pintu lemari saya buka dan tampak Ayah tersenyum dengan manisnya kepada saya. Wajah beliau saat itu cerah sekali dan sangat berbeda dari keadaan yang hampir satu jam yang lalu. Sambil diiringi tangisan saya yang panjang, dengan lembut Ayah mencium kening dan mengelus kepala saya. Ayah juga membujuk agar saya kembali ke atas lagi. Akhirnya sisa sore itu hingga magrib, suasana menjadi lebih baik. Ayah tidak menguji saya lagi, tetapi hanya terus menerangkan secara lebih perlahan dan dengan lebih banyak senyum. Pengalaman itu terus membekas, sebab semenjak sore itu, setiap minggu saya mendapat dua kali pengajaran mengaji. Sekali dari ustadzah dan sekali dari Ayah. Untuk seterusnya saya sudah tidak pernah dikatakan “bodoh” lagi, meskipun ketololan toh tetap sering saya lakukan. Paling-paling Ayah hanya mengatakan, “Akh, salah, harusnya…” Mungkin kemudian Ayah berpikir bahwa daya tangkap anak kecil tidaklah sama dengan daya tangkap mahasiswa-mahasiswa Ayah. Juga cara mendidik anak-anak haruslah dengan lebih sabar. Dan yang penting tidak boleh cepat membuat anak putus asa dengan perkataan “bodoh”. Rasanya seumur hidup saya baru kali itulah saya dibuat menangis oleh Ayah. Sungguh, beliau adalah orang yang jarang marah kepada anak-anak. Gemala Rabi’ah Chalil Hatta, Pribadi Manusia Hatta, Seri 2, Yayasan Hatta, Juli 2002