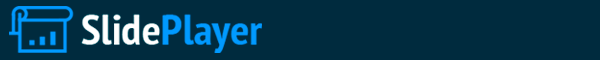
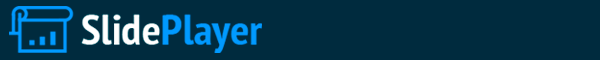
Bu Diro yang “Lebih Populer” Tentang kesederhanaan Bung Hatta, yang juga sering merupakan kontras dengan tokoh-tokoh tertentu pada zamannya, tidak sedikit contoh-contoh yang dapat kita utarakan. Tetapi untuk kali ini saya hanya akan menyebut satu contoh saja, yaitu tatkala saya (waktu itu sebagai gubernur Provinsi Sulawesi), bersama istri mengantarkan Wakil Presiden Moh. Hatta keliling ke daerah Sangihe-Talaud di Sulawesi Utara, pada awal tahun 1952. Dengan naik kapal perang yang dikemudikan oleh perwira-perwira muda ALRI kita, setelah kami mengunjungi pulau-pulau Sangihe Besar, Talaud, Karakelang, dan Siau, kami menuju ke arah utara sampai dekat perbatasan dengan Republik Filipina. Setelah kami singgah sebentar di Pulau Marore, kami kemudian berlabuh di muka Pulau Miangas, yang dulu bernama Las Palmas. Dalam sejarah Perang Dunia II pulau ini terkenal, karena kalau waktu itu kebetulan sebuah kapal Amerika lewat di dekatnya, penduduknya segera mengibarkan Stars and Stripes (bendera Amerika Serikat). Sebaliknya apabila yang lewat itu kapal Jepang, maka segera pula Hinomaru (bendera Jepang) dikibarkan. Setelah rombongan wakil presiden naik daratan, kami harus melewati sebuah gapura yang ada tulisannya dengan huruf-huruf besar: “Selamat datang Wakil Mahkota Indonesia!” Wakil Mahkota! Yang seharusnya: Wakil Presiden. Dan kemudian “tua-tua kampung” tampil ke depan dan menyambut rombongan dengan pidato singkat dalam bahasa Inggris dengan slang (dialek) Filipina! Memang pengaruh Filipina di pulau ini waktu itu tampak dan terasa sekali, baik dari pakaian gadis-gadisnya maupun dari tari-tarian yang disuguhkan pada kami. Kami suami-istri, selaku pengantar Bung Hatta sebagai tamu agung, tentu saja selalu berusaha agar beliau yang menerima penghormatan-penghormatan dari penduduk, bukan orang lain. Terutama Bu Diro selalu memberi isyarat-isyarat, agar rakyat setempat dalam segala hal mendahulukan Bung Hatta. Tetapi, mungkin disebabkan karena pengaruh Filipina yang begitu kuat, atau mungkin karena Bu Diro waktu itu merupakan satu-satunya wanita dalam rombongan kami itu, timbul gejala bahwa penduduk setempat sering tidak menyadari perbedaan antara seorang Kepala Negara No. 2 dan istri Kepala Daerah ini! Dan bagaimana reaksi Bung Hatta? Beliau hanya tersenyum saja dan sering kali membiarkan penduduk mengelu-elukan Bu Diro lebih dari beliau sendiri! Hanya seorang tokoh yang memang memiliki watak yang sederhana yang dapat bertindak seperti Bung Hatta itu! Tanpa merasa “terinjak jari kakinya” sama sekali. Sebagai orang yang sering mengikuti pidato-pidato Bung Hatta, ada lagi pembawaan beliau yang terasa oleh orang banyak, yaitu wataknya yang tidak mengenal putus-asa. Tidak suka menyerah kalah walaupun setelah mengalami pukulan-pukulan dari pihak lawan secara bertubi-tubi. Satu hal yang sungguh pantas ditiru oleh kita! Kemudian saya ingin menyoroti satu lagi dari Bung Hatta sebagai manusia, yaitu kesetiaannya pada kawan-kawan. Lihat saja sekretaris pribadinya, Sdr. I. Wangsa Widjaja dan Sdr. W.I. Hutabarat, yang bisa kita sebut “sekretaris abadi”. Padahal mereka berdua itu bukan keluarga hanya teman seperjuangan saja! Bahwa Sdr. I Wangsa Widjaja telah tahan sampai hampir setengah abad menjadi “werangka” Bung Hatta, ya bahkan akhirnya seolah-olah menjadi tweede ik Bung Hatta (”Aku kedua” bagi Bung Hatta), pasti disebabkan karena Bung Hatta yang sembilan tahun lebih tua dari sekretarisnya itu selalu bersikap sabar, bukan pendendam, lekas dan suka memberi maaf dan memiliki jiwa kebapaan. Pak Diro, Pribadi Manusia Hatta, Seri 7, Yayasan Hatta, Juli 2002